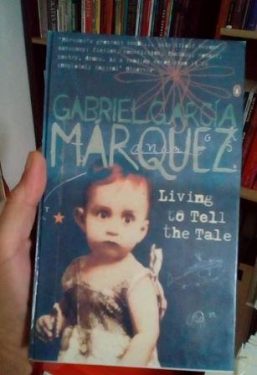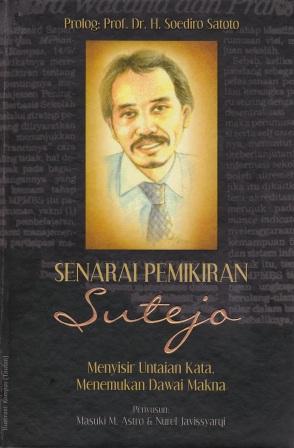Pembuka
Hermeneutik bukanlah sebuah istilah modern, melainkan sebuah istilah kuno yang dapat ditelusuri sampai zaman Yunani. Istilah ini terkait dengan Hermes, tokoh dalam mitologi Yunani yang bertindak sebagai utusan dewa-dewa untuk menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Hermeneutik dalam bahasa Inggris hermeneutics berasal dari kata Yunani hermeneuein yang berarti menerjemahkan atau bertindak sebagai penafsir.[1] Di dalam kegiatan menerjemahkan sebuah teks, kita harus memahami lebih dahulu teks tersebut. Menerjemahkan bukan hanya sekedar menukar kata asing dengan kata dalam bahasa kita, melainkan juga memberikan penafsiran. Dengan demikian, hermeneutika diartikan sebagai sebuah kegiatan atau kesibukan untuk menyingkap makna teks. Pada perkembangan kemudian, teks dimengerti secara luas sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, segala sesuatu yang mengandung jejaring makna atau struktur simbol-simbol adalah teks. Perilaku, tindakan, norma, mimik, tata nilai, isi pikiran, percakapan, benda-benda kebudayaan, obyek-obyek sejarah dan seterusnya adalah teks. Karena semua hal yang berhubungan dengan manusia dimaknai olehnya, yaitu kebudayaan, agama, masyarakat, negara dan bahkan seluruh alam semesta, semuanya adalah teks. Jika demikian, hermeneutika diperlukan untuk memahami semua itu.[2]
Sebelum konsep hermeneutika diperbaharui secara radikal oleh Heidegger dalam bukunya Sein und Zeit/Being and Time, pada mulanya hermeneutika dimaknai sebagai penafsiran teks kuno atau tafsir kitab suci yang digawangi Schleiermacher dan sebagai pendasaran metodologis yang bersifat universal untuk ilmu-ilmu sosial yang dirintis Wilhelm Dilthey. Saat itu, hermeneutika belum menjadi perhatian atau tema pokok filsafat. Hermeneutika menjadi sebuah kajian filosofis yang berbobot, baru mengemuka lewat terbitnya buku magnum opus Hans Georg Gadamer –selanjutnya disebut Gadamer- yang berjudul Wahrheit und Methode/Truth and Method. Penulis dalam esai ini mengelaborasi hermeneutika Gadamer, yang meliputi kritik Gadamer terhadap teori hermeneutik sebelumnya, apa yang menjadi pokok-pokok hermeneutik Gadamer, implikasi filosofis hermeneutik Gadamer dan kritik Habermas terhadap hermeneutik Gadamer.
- Kritik Gadamer terhadap Teori Hermeneutik Sebelumnya.
- Pokok-pokok Hermeneutik Gadamer
- Implikasi filosofis hermeneutik Gadamer
- Kritik Habermas Terhadap Hermeneutik Gadamer.
a. Kritik Terhadap Romantisme Schleiermacher.
Hermeneutik Schleiermacher memusatkan diri pada upaya memahami keasingan dalam teks-teks kuno. Schleiermacher berkehendak untuk menghadirkan kembali makna dari masa silam seutuh-utuhnya agar kesalahpahaman dengan pembaca masa kini dapat diatasi. Tindakan memahami diandaikan sebagai rekonstruksi atas produksi teks atau makna yang seolah bisa steril dari keterlibatan penafsirnya dalam kekiniannya. Dengan demikian, hermeneutik romantis Schleiermacher dikategorikan sebagai hermeneutik reproduktif.[3]
Yang dilupakan oleh teori ini, menurut Gadamer, adalah pengarang dan pembacanya masing-masing sudah senantiasa bergerak di dalam wilayah saling-pemahaman yang berbeda. Tindakan memahami, lanjut Gadamer, bukanlah sebuah representasi atas makna dari masa silam, melainkan sebuah peleburan antara cakrawala/horizon masa silam dari pengarang dan horizon masa kini dari pembaca.[4]
b. Kritik Terhadap Historisme[5] Wilhelm Dilthey
Menurut Gadamer, Wilhelm Dilthey –selanjutnya disebut Dilthey- belum keluar sepenuhnya dengan cara pandang cartesian yang dikritiknya. Dua hal yang dikemukakan Gadamer untuk mengkritik Dilthey. Pertama, Dilthey berpandangan bahwa kita ditentukan sejarah, maka kita dapat mengetahui sejarah sebagai fakta. Dalam arti ini lalu pengetahuan sejarah berciri universal, yaitu melampaui sejarah konkret. Pandangan ini bertentangan dengan historisitas itu sendiri yang mengandaikan bahwa kita manusia bergerak di dalam sejarah dan tidak mengatasinya. Kedua, kesadaran historis Dilthey masih dipahami sebagai kesadaran akan sejarah, bukan sebagai kesadaran dalam sejarah. Kesadaran historis Dilthey merupakan hasil refleksi yang seolah-olah bisa keluar dari sejarah, seperti pandangan burung di atas bumi dan dengan cara itu menemukan fakta obyektif. Padahal, menurut Gadamer, pengetahuan kita sendiri menyejarah. Ada yang lebih primordial daripada kesadaran atau pengetahuan akan sejarah, yakni kesadaran yang ditentukan dan dipengaruhi oleh sejarah.
Dengan mengkritik kedua tokoh tersebut, Gadamer berpendapat bahwa pembaca tidak dapat kembali ke masa silam untuk menemukan makna asli yang dimaksud penulis teks. Kesadaran kita juga tidak berada di luar sejarah, melainkan bergerak di dalam sejarah, sehingga pemahaman kita juga dibentuk oleh sejarah. Dengan ungkapan lain, pemahaman kita berada di dalam horizon tertentu. Setelah mengkritik Schleiermacher dan Dilthey, pada paragraf berikutnya, penulis menjelaskan solusi yang ditawarkan Gadamer melalui subbab kedua: pokok-pokok hermeneutik Gadamer.
Sebelum masuk penjelasan tentang pokok-pokok hermeneutik Gadamer, penulis lebih dahulu menjelaskan keterpengaruhan teori hermeneutik Gadamer oleh sang Guru, Heidegger. Kerangka hermeneutik Gadamer berangkat dari paradigma Hiedegger tentang dimensi ontologis manusia, yakni cara berada Dasein. Gadamer mengembalikannya pada interpretasi pada umumnya yang juga dilakukan dalam ranah keseharian. Seseorang yang mencoba untuk memahami tak terlindung dari distraksi makna-makna yang telah ada sebelumnya yang tidak berasal dari hal-hal itu sendiri. Bila memahami selalu melibatkan makna yang telah ada sebelumnya, suatu pra-struktur pemahaman, tidak akan ada interpretasi obyektif sebagaimana dikejar Schleiermacher dan Dilthey. Pra struktur pemahaman ini diadaptasi Gadamer menjadi konsep prasangka. Prasangka ini bersumber dari otoritas dan tradisi. Manusia, menurut Gadamer tidak bisa keluar dari tradisi, tiada pemahaman yang bekerja sendiri, tanpa prasangka, karena dalam setiap pemahaman bekerja unsur-unsur dari otoritas dan tradisi.
Pra-struktur pemahaman Heidegger yang sudah disinggung di atas itu terdiri dari tiga unsur yaitu Vorhabe, Vorsicht dan Vorgriff. Menurut Gadamer, Heidegger mendiskusikan lingkaran hermeneutik pertama-tama bukan sebagai usaha pemahaman praktis, melainkan dimaksudkan untuk memberikan deskripsi cara pencapaian pemahaman melalui interpretasi. Heidegger mengatakan bahwa jika seseorang ingin memahami sesuatu, ia membawa latarbelakang tradisi yang telah ia miliki sebelumnya. Unsur pertama dalam hermeneutik ini disebut dengan Vorhabe (Fore-have). Selanjutnya, dalam membuat penafsiran, orang itu selalu dibimbing oleh cara pandang tertentu. Maka dari itu dalam setiap tindak pemahaman ia selalu didasari oleh apa yang telah dilihat sebelumnya. Itulah unsur yang dinamakan Vorsicht (Fore-sight). Unsur ketiga yang menjadi syarat pemahaman adalah konsep-konsep yang memberi kerangka awal yang diistilahkan dengan Vorgriff (Fore-conception).[6] Ketiga unsur inilah yang dikembangkan Gadamer menjadi pokok-pokok hermeneutiknya sebagai berikut:
a). Peleburan Cakrawala (Fusion of Horizon).
Memahami sesuatu, menurut Gadamer, bukanlah sebuah representasi atas makna dari masa silam, transposisi diri atau teman sezaman dengan pengarang di masa lampau seperti yang diusulkan Schleiermacher cukup problematis, karena kita, sebagai pembaca, sudah mempunyai suatu cakrawala untuk menempatkan diri kita sendiri dalam situasi historis. Oleh karena itu, menurut Gadamer, setiap proses pemahaman adalah sebuah peleburan antara cakrawala masa silam dari pengarang dan cakrawala masa kini dari pembaca. Kedua cakrawala itu tidak berada dalam posisi via a vis. Keduanya hanya dapat dimengerti kalau dilihat hubungan yang ada di antara mereka. Mencari makna dari masing-masing per se adalah tindakan sia-sia. Dengan demikian, dalam kesadaran sejarah orang dituntut untuk bersikap waspada atas keunikan cakrawalanya sendiri yang pada gilirannya mampu membedakan dirinya dari cakrawala tradisi meskipun disadari bahwa tidak akan pernah ada suatu rekonstruksi historis secara menyeluruh.
b). Sejarah Pengaruh (Effective History Consciousness)
Memahami sejarah tidak hanya berarti bahwa kita memahami fenomena sejarah, seperti misalnya memahami isi karya-karya masa silam, melainkan juga memahami pengaruh-pengaruh karya itu dalam sejarah. Yang disebut terakhir ini kurang mendapat perhatian Dilthey dan justru diangkat menjadi pokok pemikiran Gadamer sekaligus kritiknya terhadap historisme Dilthey. Istilah sejarah pengaruh mengacu pada keterlibatan kita dalam sejarah, yakni suatu situasi yang di dalamnya kita sebagai pelaku-pelaku sejarah tidak melampaui sejarah.
Terkait dengan penjelasan sejarah pengaruh, Budi Hardiman memberikan ilustrasi begini: seorang peneliti sejarah memahami fenomena sejarah, seperti misalnya peristiwa gerakan 30 September 1965, dengan mengambil jarak. Hasil pemaparannya diklaim sebagai obyektif karena tanpa keterlibatan peneliti di dalamnya. Pengetahuan obyektif tentang sejarah itulah kesadaran sejarah yang dibanggakan pencerahan Eropa sebagai prestasinya. Gadamer melawan kepongahan intelektual seperti itu. Menurutnya, peneliti dengan kesadaran sejarah itu justru tidak menyadari bahwa pengambilan jarak yang dia lakukan saat meneliti itu merupakan sebuah situasi hermeneutis yang di dalamnya ia juga berada di bawah pengaruh-pengaruh zamannya sendiri. Paparan sejarah seorang peneliti mencerminkan sedikit banyak kekuatan-kekuatan pengaruh, seperti kepentingan-kepentingan ideologis, politis, kultural, ataupun ekonomis, yang mengarahkan penelitiannya.[7]
Gadamer berpendapat bahwa interpretasi bukanlah rekonstruksi ataupun representasi makna dari masa silam, melainkan interseksi antara tradisi dan kekinian penafsir sedemikian rupa sehingga dihasilkan sesuatu yang baru. Hermeneutik tidak berciri reproduktif, melainkan produktif. Dengan demikian, bagi Gadamer, pemahaman terhadap teks merupakan hasil peleburan cakrawala-cakrawala. Dari pendapat tersebut mengimplikasikan bahwa kebenaran tidak hanya bersifat historis, yakni bergerak dalam ruang dan waktu, melainkan juga tidak mungkin dicapai suatu kebenaran final dan absolut.[8]
Pandangan itu mengandaikan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu untuk ditemukan, seolah-olah suatu kebenaran utuh telah ada dan menanti untuk ditemukan melainkan sesuatu yang dibuat. Kata “dibuat” di sini bukan dalam pengertian direkayasa misalnya lewat retorika, melainkan dalam pengertian bahwa praktik-praktik otoritas dan tradisi yang mengisi horison hermeneutis itu yang mengisi kebenaran. Kebenaran muncul dari hubungan-hubungan kompleks tradisi dan otoritas yang membentuk horizon pemahaman kita.[9]
Habermas mengkritik hermeneutik Gadamer terutama terkait tradisi dan klaim universal dari hermeneutik. Menurut Gadamer, konsep memahami bergerak di dalam tradisi dan otoritas tertentu, karena kita adalah makhluk sejarah yang memahami dalam horizon tradisi tertentu, yang tentu dijaga oleh otoritas tertentu. Memahami tak lain daripada kesepahaman atau persetujuan dengan tradisi. Kita tidak dapat melampaui tradisi karena kita tidak mungkin melampaui tradisi. Singkatnya, Gadamer mengandaikan adanya konvergensi antara hermeneutik dan tradisi. Tidak setuju dengan Gadamer, Habermas berargumentasi bahwa tradisi tidak hanya untuk diteruskan, kita dapat juga putus darinya karena kita tidak bersikap pasif terhadap tradisi dan otoritas, melainkan juga bersikap kritis, sehingga penerimaan atas legitimitas tradisi juga tergantung pada refleksi kita atasnya.
Yang dipersoalkan Habermas bukan elemen tradisi dan otoritas dalam pemahaman, sesuatu yang dalam keadaan normal bisa saja tanpa masalah, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan di dalamnya. Jadi, Gadamer terlalu fokus pada proses pemahaman dan mengabaikan fakta bahwa pemahaman itu juga dikendalikan oleh kekuasaan. Habermas memasukkan dimensi kekuasaan sebagai sebuah unsur sentral dalam memahami teks. Menurut Habermas, bahasa bukanlah sesuatu yang netral, karena bahasa juga dapat menjadi medium kekuasaan dan dapat dipakai untuk membenarkan hubungan-hubungan kekuasaan. Hermeneutik sebagai pemakaian bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, menurut Habermas hanyalah sebuah momen dari proses sosial yang terkait dengan kekuasaan terorganisasi. Bila kita mengabaikan elemen ini, hermeneutik hanya akan terjebak ke dalam sikap konservatif dan bahkan naif membenarkan tatanan yang ada.
Kritik Habermas terhadap gagasan Gadamer tentang hermeneutik universal bahwa hermeneutik tidak dapat diterapkan di semua pengetahuan, misalnya tidak berlaku di ilmu alam. Ada batas lain yang dapat ditemui oleh hermeneutik sehingga klaim universalitasnya sulit dipenuhi yaitu ketika seorang penafsir berhadapan dengan teks-teks yang tidak lazim (abnormal), maksudnya bahasa dan perilaku yang tidak dimengerti oleh penutur atau pelakunya sendiri. Habermas menunjuk kepada kasus psikopatologis dan kasus perilaku kolektif hasil indoktrinasi. Kedua kasus tersebut, menurut Habermas, mengalami komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.
Solusi Yang Ditawarkan: Hermeneutik Kritis[10]
Mengatasi kedua kasus tersebut, Habermas mengajukan hermeneutika kritis dengan memakai metode psikoanalisis Freud dan kritik ideologi Marx. Habermas membedakan hermeneutik biasa dengan psikoanalisis. Hermeneutik biasa menghadapi teks-teks yang memuat ingatan subjektif tentang sejarah hidupnya dalam kondisi-kondisi normal. Di sini penulis teks dipandang mengetahui dirinya dan secara sadar mengungkapkan struktur-struktur simbolis dalam teks itu. Seorang penafsir lalu berupaya memahami teks itu “dari dalam” untuk mengetahui apa yang dimaksudkan. Makna-makna struktur simbolis itu dipelajari dengan kecurigaan hanya terhadap intervensi tak sadar dari kondisi-kondisi eksternal, misalnya konteks sejarah si penulis sendiri. Yang dihadapi psikoanalisis justru teks-teks yang mencurigakan dari segi internal penulis. Struktur-struktur simbolis yang terungkap tidak dengan sadar dimaksudkan demikian, karena si penulis atau subyek mengalami gangguan-gangguan internal atau simtom-simtom neorosis. Struktur-struktur simbolis yang diungkapkan telah terdistorsi dari maksud sesungguhnya oleh penyakitnya. Dengan demikian, jika hermeneutik biasa menghadapi language game yang berfungsi baik, psikoanalisis menghadapi language game yang telah menjadi kacau susunannya.
Dengan adanya unsur-unsur tak sadar dan terselubung itu, psikoanalisis melampaui hermeneutik biasa. Psikoanalisis bermaksud menembus makna-makna simbolis yang ada di permukaan yang tidak dicurigai oleh hermeneutik biasa sampai menemukan motif-motif tak sadar dari subyek. Dalam psikoanalisis, digabungkan dua metode lain menjadi satu yaitu analisis bahasa dan penelitian psikologis. Karena itu, metode yang ditemukan Freud ini tidak dapat disamakan dengan hermeneutik biasa dan menurut Habermas, lebih tepat disebut hermeneutik dalam atau hermeneutik kritis. Sebagai hermeneutik kritis, psikoanalisis berusaha menerjemahkan teks itu sampai dapat dipahami baik oleh orang lain maupun subyek itu sendiri. Dengan kata lain, menurut Habermas, psikoanalisis menerjemahkan ketidaksadaran menjadi kesadaran. Dalam praktek klinis, hermeneutik biasa tidak akan mampu menafsirkan struktur simbolis yang dihasilkan subyek karena hermeneutik biasa hanya ingin mengatasi kesulitan dalam komunikasi dua subyek yang terpisah secara historis, kultural, dan sosial dan bukan terpisah oleh taraf normalitas psikis. Dalam keadaan patologis, subyek tidak akan mampu mencapai saling pemahaman timbal balik karena struktur simbolis yang seharusnya rasional terdistorsi secara psikis. Komunikasi yang terganggu ini tidak memerlukan seorang penafsir hermeneutis biasa, melainkan seorang analis yang mengajari subyek untuk dapat memahami bahasanya sendiri. Analis mengajarnya untuk membaca teks yang telah didistorsikannya sendiri lalu mengajarinya bagaimana menerjemahkan struktur-struktur simbolis privat itu ke dalam bahasa publik.
Habermas memahami tekhnis analitis dari psikoanalisis itu termasuk sebagai refleksi diri. Refleksi diri menurut Habermas adalah tindakan rasio yang menyebabkan ego dapat membebaskan diri dari dogmatisme atau kesadaran palsu. Di dalam refleksi diri, ego menjadi transparan terhadap dirinya sendiri dan terhadap asal usul kesadarannya sendiri. Di dalam kegiatan refleksi, kita sebagai ego tidak hanya memiliki kesadaran baru tentang diri kita sendiri melainkan bahwa kesadaran baru itu mengubah hidup eksistensial kita sendiri. Tindakan mengubah hidup itu adalah tindakan emansipatoris. Karena di dalam refleksi diri kesadaran dan tindakan emansipatoris itu menyatu, dalam kegiatan refleksi, rasio kita langsung menjadi praktis. Refleksi diri, lanjut Habermas, adalah intuisi sekaligus emansipasi, pemahaman sekaligus pembebasan dari ketergantungan dogmatis. Dengan demikian, refleksi diri adalah kegiatan kognitif yang memuat kekuatan emansipatoris karena kegiatan ini didorong oleh kepentingan yang inheren di dalam rasio kita sendiri, yaitu kepentingan emansipatoris.
Habermas mengungkap tiga alasan lain kenapa pengetahuan analitis itu dikategorikan sebagai refleksi diri. Pertama, pengetahuan analitis mencakup baik unsur kognitif maupun afektif dan motivasional. Pengetahuan semacam ini adalah kritik karena didorong oleh pengetahuan dan kebutuhan akan perubahan praktis. Keadaan patologis pasien tak lain dari kesadaran palsu yang dapat dihancurkan hanya dengan kehendak, dengan apa yang disebut Habermas sebagai passion for critique. Di sini kepentingan pasien untuk sembuh, kepentingan emansipatoris, merupakan syarat suksesnya terapi. Dengan kata lain, suksesnya terapi bukan terutama disebabkan oleh pengarus analis, melainkan pada refleksi diri dari pasien sendiri. Kedua, dalam proses terapi ditekankan agar pasien tidak menghubungkan penyakitnya dengan penyakit fisik melainkan harus memandangnya sebagai bagian dari kediriannya sendiri. Dalam proses itu, ego si pasien mengenal dirinya sebagai kedirian yang terasing karena penyakitnya dan ia harus mengidentifikasikan diri dengan kedirian yang terasing itu. Dalam hal ini pasien mengemban tanggung jawab moral atas penyakitnya sendiri. Dan di sini, menurut Habermas, rasio teoritis dan rasio praktis tidak dapat dipisahkan karena terapi merupakan suatu moral insight. Ketiga, dalam proses terapi itu, analis membuat dirinya sendiri sebagai alat pengetahuan, tidak dengan menyingkirkan subyektifitasnya, melainkan dengan suatu pelaksanaan terkendali. Untuk menyembuhkan pasien, analis menghayati peranan si pasien, yaitu peran seorang penderita yang sedang berusaha membebaskan diri dari penyakitnya. Dengan kata lain, analis harus sungguh terlibat secara mendalam di dalam pengalaman-pengalaman pasiennya. Melihat proses analitis tersebut, tampaklah bahwa pengetahuan analitis bukannya tanpa kepentingan karena terapi diperoleh sejauh pasien didorong oleh kepentingan emansipatoris untuk sembuh dan sebaliknya analis didorong kepentingan yang sama untuk membebaskan pasien. Sebagai refleksi diri, psikoanalisis menyatukan kognisi dan afeksi, rasio teoritis dan rasio praktis dan akhirnya menyatukan pengetahuan dan kepentingan.[11]
Sampai di sini, Habermas telah menunjukkan bagaimana psikoanalisis menjadi contoh ilmu kritis pada level individual. Habermas juga mencoba mengintegrasikan psikoanalisis Freud ini ke dalam materialisme sejarah Karl Marx untuk menunjukkan bagaimana ilmu kritis yang masih ada di dalam bentuk program itu diterapkan dalam realitas sosial. Di atas secara implisit telah terkandung suatu persoalan yaitu tentang normalitas psikis. Masalah ini menarik karena menjadi titik tolak bahasan Habermas tentang psikoanalisis sebagai kritik sosial. Habermas melihat adanya kesamaan dan perbedaan antara Marx dan Freud dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. Meskipun di dalam istilah yang berbeda, Freud juga membedakan kekuatan-kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi. Seperti Marx memahami masyarakat, Freud memahami kebudayaan sebagai sarana manusia untuk melampaui taraf kondisi-kondisi eksistensi hewan. Manusia melampaui hewan dalam dua aspek. Pertama, manusia memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan alam dan menimba hasilnya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Kedua, untuk mendistribusikan hasil-hasil alam ini manusia mengatur interaksinya satu sama lain melalui pranata-pranata sosial. Kedua aspek ini saling tergantung dan tumpang tindih karena tiga hal. Pertama interaksi secara mendalam dipengaruhi oleh pemuasan naluri-naluri yang dimungkinkan oleh hasil-hasil alam itu. Kedua, manusia dapat memakai sesamanya seperti ia memakai alam, entah memperlakukannya sebagai obyek kerja entah sebagai obyek seksual. Ketiga, setiap individu sesungguhnya adalah musuh kebudayaan meskipun kebudayaan merupakan kepentingan manusiawi universal untuk pemeliharaan diri kolektif. Menurut Habermas, pada alasan ketiga inilah terdapat perbedaan antara Freud dan Marx.
Berbeda dengan Marx yang memandang pranata-pranata sosial sebagai penataan kepentingan-kepentingan yang memungkinkan berfungsinya sistem kerja sosial, Freud memandangnya dalam kaitannya dengan represi atas dorongan-dorongan naluriah, maka pranata sosial adalah musuh individual juga. Penataan kepentingan dalam pandangan Marx berakar pada struktur kelas dan terdistorsi oleh struktur itu sehingga keuntungan dan kewajiban sosial didistribusikan menurut struktur kelas. Represi sosial dipaksakan secara universal tak tergantung pada struktur kelas. Dalam hal-hal di atas, menurut Habermas, terdapat perbedaan konteks pemahaman atas penataan institusional antara Freud dan Marx. Jika Marx memahaminya sebagai penataan pembagian kerja, Freud memahaminya sebagai penataan tekanan atas pembagian kerja sosial itu. Dengan kata lain, Freud tidak memahaminya dalam konteks tindakan instrumental, melainkan dalam konteks interaksi. Untuk menjaga kelangsungan sistem pemeliharaan diri kolektif itu yang perlu diatur bukanlah kerja, melainkan tekanan atas kerja itu.
Berbicara tentang materialisme sejarah Marx, Habermas menunjukkan bahwa Marx tidak menghasilkan ilmu sebagai kritik karena memahami aktivitas revolusioner yang mendorong proses pembentukan diri dalam konteks tindakan rasional bertujuan. Pengetahuan yang dihasilkan dengan paradigma kerja bukanlah pengetahuan refleksif, melainkan produktif. Menurut Habermas, kegiatan revolusioner itu harus dipahami dalam konteks tindakan komunikatif. Hal ini, menurut Habermas, tidak dipahami Marx dan kekurangan Marx ini dapat diatasi oleh teori Freud. Freud memahami pranata-pranata kekuasaan dan ideologi-ideologinya sebagai tindakan komunikatif yang terdistorsi. Pranata-pranata telah menukarkan kekuasaan eksternal dengan tekanan internal permanen yang menghasilkan komunikasi yang terdistorsi yaitu ideologi-ideologi sebagai kepuasan substitusi.[12]
Mengapa Marx tidak dapat memahami kekuasaan dan ideologi sebagai komunikasi yang menyimpang? Marx mendasarkan diri pada pengandaian bahwa manusia membedakan dirinya dari hewan saat ia mengubah tingkah laku adaptifnya menjadi tindakan instrumental. Dari pengandaian ini, ia memahami sejarah sebagai penataan fisik atas tindakan-tindakan instrumental. Karena itu pula tindakan revolusioner emansipatoris dipahami dalam kategori tindakan rasional-bertujuan. Berbeda dari Marx, Freud mendasarkan diri pada pengandaian bahwa manusia membedakan dirinya dengan hewan saat ia berhasil mengubah tingkah laku yang dikendalikan oleh naluri-naluri menjadi tindakan komunikatif. Jika Marx meletakkan kerja sebagai dasar alamiyah dari sejarah, yang oleh Freud dipahami sebagai dasar alamiyah dari sejarah adalah penataan fisik atas tindakan-tindakan komunikatif dalam kategori-kategori dorongan-dorongan naluriyah yang berlebihan dan penyalurannya. Apa tujuan dari langkah-langkah perkembangan masyarakat itu? Di sini kita sampai pada semacam cita-cita atau utopia yang termuat dalam teori kritis Habermas tentang masyarakat, yaitu terciptanya suatu masyarakat yang berinteraksi dalam lingkup komunikasi bebas penguasaan.
Dengan demikian bagi hermeneutik kritis yang digagas Habermas, memahami bukanlah sekedar mereproduksi makna sebagaimana Schleiermacher dan Dilthey dan juga bukan sekedar memproduksi makna baru yang terarah ke masa depan, seperti pada Heidegger dan Gadamer, melainkan membebaskan penulis dari komunikasi yang terdistorsi secara sistematis yang telah menghasilkan teksnya. Lazimnya, hermeneutik bertujuan agar pembaca memahami teks, tetapi hermeneutik kritis bertujuan agar penulisnya memahami teks yang ditulisnya sendiri sehingga ia bebas dari distorsi-distorsi yakni dalam psikoanalisis memperoleh kesembuhan dan dalam kasus kritik ideologi memperoleh otonomi. Hermeneutik kritis melampaui hermeneutik biasa dalam arti bahwa metode ini berupaya keras untuk menemukan motif yang tidak disadari pelakunya. Memahami bagi Habermas sebagai emansipasi (praksis pembebasan). Memahami secara kritis metodologis merupakan praksis pembebasan dari kesepahaman semu hasil dominasi untuk mencapai kesepahaman rasional yang bebas dominasi.[13]
***
Catatan:
[1] Richard E Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 16-17.
[2] Budi Hardiman, Seni Memahami (Jakarta: Kanisius, 2015), h. 11-12.
[3] Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi, h. 220.
[4] Edi Mulyono, Belajar Hermeneutika Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies (Yogyakarta: Ircisod, 2013), h. 151-152.
[5] Historisme adalah pandangan yang diwakili madzhab sejarah yang mewarnai lanskap intelektual Jerman abad ke-19 lewat para filolog dan penulis sejarah seperti August W. Boeck, Leopold von Ranke. Madzhab ini melawan filsafat sejarah Hegel yang menurut mereka terlalu metafisis dan ingin mendasarkan sebuah penelitian sejarah yang empiris. Sejarah ingin dipahami tidak dari skema metafisis dan teleologis, melainkan dari peristiwa dan konteksnya yang empiris. Menurut pandangan ini peristiwa-peristiwa sejarah hanyalah ungkapan zamannya yang dapat diakses sebagai fakta-fakta obyektif. Selengkapnya baca Hardiman, Seni Memahami, h. 164-165.
[6] Agus Darmaji, “Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer,” Jurnal Refleksi Vol. 13 (2013): h. 473.
[7] Hardiman, Seni Memahami, h. 176-177.
[8] Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi, h. 265-269.
[9] Hardiman, Seni Memahami, h. 185.
[10] Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas (Yogyakarta: Buku Baik, 2004), h. 218.
[11] Mohammad Anas, Rekonstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Analitis Kritis-Dialogis Jurgen Habermas Dan M. Abid Al-Jabiri (Malang: UB Press, 2018), H. 129-131.
[12] Listiyono Santoso, Epistemologi Kiri (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2013), H. 240-241.
[13] Hardiman, Seni Memahami, h. 230-231.
_____________
*) Fuad Nawawi: adalah seorang calon doktor pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sehari-hari ia masih mengajar mengaji di kampungnya, di samping itu ia masih sempat belajar menulis esai pada Akademi Menulis-Dunia Sastra Kita.